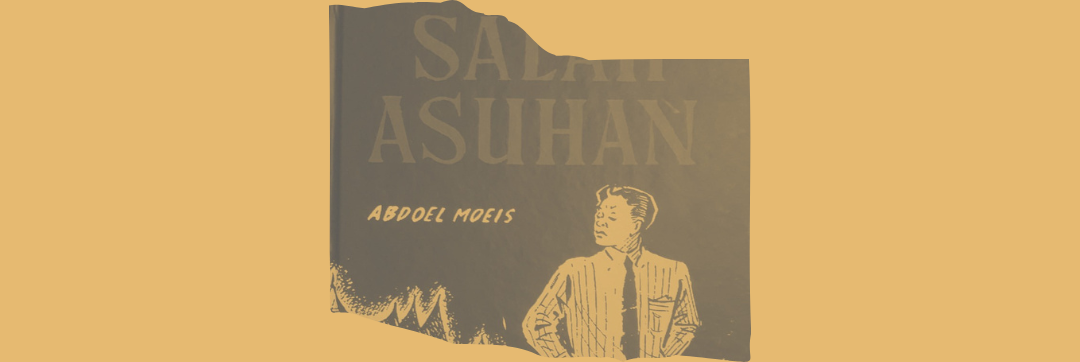Balai pustaka secara resmi didirikan pada tahun 1917 yang sebelumnya bernama Taman Bacaan Rakyat atau Volksletuur (1908). Balai Pustaka merupakan salah satu lembaga yang menjadi bagian dari politik etis/balas budi pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia dalam bidang edukasi. Menurut Tassai, pemerintah Belanda melihat banyak bacaan-bacaan yang dinilai tidak sesuai moral dan dinilai dapat merusak moral bangsa (Yudiono, 2010). Berdasarkan kekhawatiran terhadap masalah ini, maka pemerintah Belanda secara cepat mengambil langkah untuk membentuk Balai Pustaka sebagai lembaga penerbit yang mengawasi dan menyediakan bacaan yang sesuai dengan moral bangsa. Akan tetapi kepedulian ini hanya sebagai alasan untuk menutupi maksud lain dari pemerintah Belanda yaitu melindungi rakyat dari pengaruh bacaan yang memantik perlawanan. Namun terlepas dari begitu kuatnya pengawasan yang dilakukan pemerintah kolonial melalui Balai pustaka, banyak penulis yang menggunakan Balai Pustaka sebagai alat untuk menyatakan kebenciannya terhadap kolonialisme.
Oleh Yakhin Maufa
Dalam novel Sitti Nurbaya karya Marah Rusli, kebencian terhadap pemerintah Belanda sangat terlihat. Marah Rusli menggunakan dua tokoh yang berseteru sebagai penggambaran akan perlawanan orang Minang terhadap pemerintah kolonial. Tokoh Datuk Maringgih mewakili orang Minang yang marah, membawa banyak protes dan kritik terhadap pemerintahan kolonial. Dalam tokoh Datuk Maringgih, Marah Rusli meluapkan rasa bencinya terhadap Belanda lewat dialog-dialog tokoh ini. Namun luapan kebencian yang dituangkan penulis bukan menjadi konflik utama yang dibawakan dalam novel ini. Konflik utama yang dibawakan adalah balas dendam sebagai akibat dari kawin paksa yang dilakukan oleh Datuk Maringgih. Jadi, walaupun kedua pihak yang berseteru mewakili orang Minang dan pemerintah kolonial, tetapi konflik utamanya bukan soal perlawanan melainkan masalah pribadi masing-masing tokoh. Cara-cara seperti ini juga digunakan oleh penulis-penulis Balai Pustaka lainnya, salah satunya Abdul Muis dalam novel Salah Asuhan.
Salah Asuhan merupakan salah satu novel yang membawa tema kawin campur, tema yang umumnya banyak dibawakan dalam novel Balai Pustaka. Apabila dalam novel Sitti Nurbaya, Marah Rusli menggunakan dua tokoh yang bertikai sebagai penggambaran dari perlawanan orang Minang terhadap pemerintah kolonial, maka dalam novel Salah Asuhan, dua tokoh yang melakukan kawin campur yaitu Corrie dan Hanafi menggambarkan akulturasi budaya yang mulai menyimpang antara budaya barat dan Minang. Dalam konflik ini, pemilihan watak masing-masing tokoh juga menunjukan kritik dan penyampaian kebencian terhadap budaya barat. Tokoh Corrie yang mewakili budaya barat memiliki watak yang manja dan pemalas. Sangat terlihat jelas bahwa pemilihan watak ini mewakili rasa benci Abdul Muis dan bangsa Indonesia. Kunci keberhasilan Abdul Muis melewati penyaringan yang ketat oleh Balai Pustaka adalah permainan latar belakang psikologi penokohan. Walaupun Abdul Muis menggambarkan tokoh Corrie sebagai tokoh yang memiliki watak kurang baik, tetapi terdapat beberapa latar belakang psikologi yang bisa “menolong” tokoh Corrie sehingga gambaran orang barat tidak selamanya jelek.
Apabila kita membaca novel ini, maka kita dapat menangkap maksud penulis membuat judul Salah Asuhan. Salah asuhan yang dimaksud berhubungan dengan latar belakang psikologi pola asuh orang tua kedua tokoh. Apabila dianalisis dengan pendekatan psikologi, Marah Rusli membuat kedua tokoh yaitu Corrie dan Hanafi memiliki pola asuh yang sama yaitu pola asuh permisif. Menurut Boumrind (1971) dalam Berk (2000), pola asuh permisif adalah kebalikan dari pola asuh otoriter yang mana orang tua terlalu membiarkan anak untuk berekspresi dan melakukan apapun yang diinginkan anak. Hal ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tuan de Busse selalu membiarkan Corrie untuk bertindak sesuka hati.
Setelah duduk di atas sofa, maka dilemparnya raketnya sampai ke sudut, dengan cepat dibukanya kedua belah sepatu tenisnya, lalu dilemparnya pula sejauh-jauhnya. Maka menghempasnyalah ia tidur di atas sofa, tanpa berkata sepatah kata jua.
Ayahnya melihat saja perangai Corrie yang berlainan dengan biasa itu.(Hal.14)
Tuan de Bussee tidak bertindak apapun terhadap tindakan yang dilakukan oleh Corrie walaupun tindakanya sudah melewati batas sebagai seorang anak perempuan. Selain itu, Tuan de Bussee terlalu memanjakan Corrie dengan tidak mengajarkan Corrie untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri. Segala pekerjaan dilakukan oleh pembantunya Simin. Dari tindak tutur yang dikeluarkan Corrie terhadap Simin juga menunjukan bahwa Tuan de Busse gagal dalam mengajarkan Corrie.
“Minta Es… sama sirop asam…, oh, tidak sirop vanili saja…” Sejurus lagi, “Simin, ah, minta air Belanda saja!” “Sama es Non?”
“Sudah tentu kerbau! Tentu saja sama es, banyak es satu pon, dua pon!” (Hal. 14)
Tindak pola asuh seperti ini yang menyebabkan Corrie tumbuh menjadi gadis yang pemalas dan manja. Pola asuh yang permisif yang diterapkan oleh Tuan de Bussee ini sebagai akibat dari dirinya sebagai seorang orang tua tunggal karena ibu dari Corrie yang meninggal.
“Hidupnya hanyalah guna anaknya saja, Nona Corrie.
Corrie baru berumur enam tahun, waktu ditinggalkan oleh ibunya.” (Hal. 11)
Tindak pola asuh yang permisif juga terjadi pada tokoh lain yaitu Hanafi. Hanafi juga kehilangan orang tua yaitu ayah sehingga Ibu Hanafi terlalu memanjakannya sebagai seorang anak laki-laki. Ibu Hanafi selalu mengikuti semua yang anaknya inginkan daripada mengajarkan kepada Hanafi cara tanggung jawab sebagai seorang laki-laki (Bab III. Bukan Bunda Salah Mengandung, Hal. 24). Karena terlalu memanjakan anaknya, ibu Hanfi pun menganggap Hanafi sebagai seorang anak kecil.
Pada hematku, kuketahui benar mana emas, mana loyang, Bu! Hanya Ibu saja yang memandang kepadaku sebagai kepada kanak-kanak. (Hal. 90)
Menurut Boumrid, dampak dari pola asuh orang tua yang permisif adalah anak bertumbuh menjadi anak yang egois, kurang taat akan aturan, dan bermasalah dalam beradaptasi. Tokoh Hanafi dalam novel ini digambarkan sebagai anak yang egois dan tidak peduli terhadap orang lain. Ketika tinggal bersama ibunya, Hanafi tidak mau untuk tinggal di dalam rumah Gadang di kota Anau sehingga dia dan ibunya pindah ke kota Solok. Segala sesuatu yang disenangi ibunya selalu dibantah oleh Hanafi. Hanafi juga bertumbuh sebagai anak yang kurang taat terhadap aturan. Dalam konteks novel ini, Hanafi tidak taat terhadap agama dan hukum adat yang berlaku. Berbeda dengan Hanafi, pola asuh permisif orang tua menyebabkan Corrie bertumbuh sebagai seorang anak yang sulit dalam beradaptasi secara mandiri. Ketika dirinya harus diperhadapkan pada kematian ayahnya, Corrie mengalami penurunan dalam hal pendidikan maupun pergaulan dengan orang-orang sekitar. Bahkan Corrie harus menerima kenyataan pahit yaitu dirinya harus tinggal kelas. Corrie sulit beradaptasi terhadap situasi yang baru yaitu hidup tanpa ayah karena selama hidupnya dirinya selalu bergantung pada ayahnya.
Penggunaan latar belakang psikologis pola asuh ini sangat membantu Abdul Muis sehingga karya miliknya dapat diterbitkan. Suara kebencian yang ingin disuarakan pun dapat tersampaikan. Walaupun dalam beberapa catatan, novel ini telah mengalami beberapa penyuntingan oleh Balai Pustaka karena penggambaran tokoh-tokohnya yang dirasa merendahkan pihak kolonial Belanda. Tokoh Corrie dianggap terlalu buruk dan seakan mewakili watak orang Belanda secara keseluruhan. Selain kekreatifan oleh Abdul Muis, ada campur tangan editor Balai Pustaka yang mengedit teks ini sehingga tidak seperti naskah aslinya. Bagian yang menggambarkan Rapiah yang gagal menikah karena kawin paksa menunjukan bahwa adanya kekurangan dari budaya timur (Wicaksono, 2017).
Novel ini menjadi sumber sejarah sekunder yang menggambarkan awal mula perlawanan terhadap pemerintah kolonial lewat perang intelektual. Novel ini membuktikan bahwa perlawanan bukan hanya lewat senjata, tetapi juga melalui karya. Novel ini hanya satu dari sekian sumber sejarah berbentuk sastra yang menjadi alat perlawanan Masih banyak novel lain milik Balai Pustaka yang bisa dianalisis sehingga dapat terkuak jejak perlawanan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan.
Referensi
References
Berk, L. E. (2000). Child Development (5th ed.). A Pearson Education Comp.
Wicaksono, A. (2017). Pengkajian Prosa Fiksi. Garudhawacana.
Yudiono, K. S. (2010). Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Grasindo.
Wicaksono, A. (2017). Pengkajian Prosa Fiksi. Garudhawacana.
Yudiono, K. S. (2010). Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Grasindo.