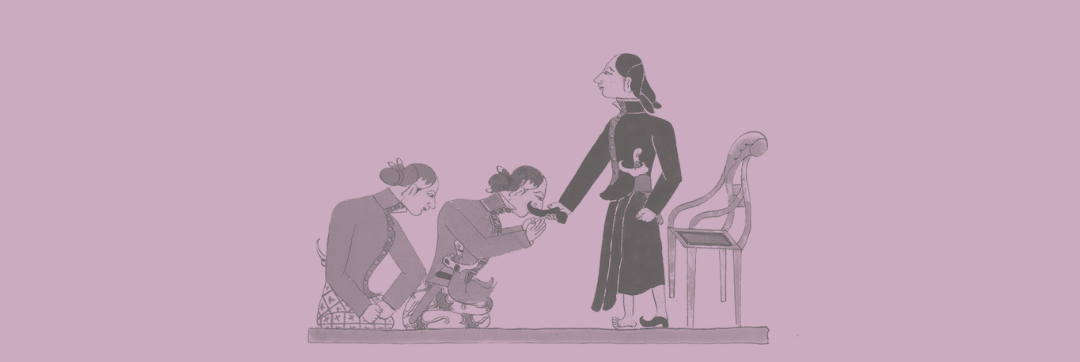Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) telah lama pergi meninggalkan Indonesia karena kebangkrutannya yang disebabkan tindakan korupsi para pejabat, misal Gubernur VOC yang melakukan perdagangan gelap untuk pribadi, alih-alih keuntungannya disetorkan ke VOC di Belanda. Hal inilah yang membawa kepada kehancuran dari perusahaan Kongsi Dagang Hindia Timur yang disebut-sebut memiliki saham dan kekayaan yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada hari ini.
Oleh Jatmika Aji
Menurut Bobby Salomos, VOC memiliki nilai saham perusahaan sebesar 78 juta Gulden Belanda dan jika diperkirakan dengan nilai saat ini sekitar US$7,9 triliun–setara dengan gabungan Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Tencent, dan Wells Fargo. Meski para penjajah telah lama pergi meninggalkan Indonesia, sifat-sifat koruptif, anti-kritik, dan sering memeras rakyat masih tetap tinggal. Hal ini bukanlah suatu kebaruan buat kita. Kalau boleh disebut juga kata korupsi adalah predikat atau nama belakang buat para pejabat.
Seperti halnya kasus baru-baru ini yang melibatkan pejabat Bea Cuka, Bupati, atau Wali Kota suatu daerah. Sebenarnya hanya beberapa yang ketahuan dari sekian kasus korupsi di Indonesia. Sudah bukan hal asing lagi bagi masyarakat Indonesia mendengar anggaran negara yang berasal dari rakyat ditilep oleh para pejabat. Setiap pergantian rezim dan siapapun presidennya, kita pasti temukan praktik korupsi dilakukan oleh pejabat.
Di Era reformasi tercatat dari tahun 2004 sampai Juli 2020, tindak pidana korupsi di Indonesia sebanyak 1.032 kasus, dengan jenis perkara korupsi yang kerap dilakukan yaitu penyuapan sebanyak 683, pengadaan barang atau jasa sebanyak 206, dan beberapa perkara lainnya seperti penyalahgunaan anggaran dan perijinan.
Sementara pada masa Orde Baru, Soeharto “si tangan besi” yang juga terlibat pembunuhan rakyat yang tidak bersalah tahun 1965-1966, bersama kroninya meraup uang negara dengan cara mengalirkan uang negara ke yayasan swasta milik pribadi. Para pihak berwenang yang seharusnya menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat justru berbalik membelakangi masyarakat dengan melakukan praktik korupsi.
Korupsi di masa kolonial
Mari kita mundur jauh ke belakang tepatnya pada abad ke-19 ketika pemerintah kolonial beserta pejabat yang menjadi perpanjangan sistem kolonial menerapkan sistem pajak yang memberatkan rakyatnya. Mulanya pada abad ke-19, Raffles memperkenalkan sistem pajak yang dapat dibayar dengan uang tunai, bukan dalam bentuk barang. Secara teoritis sistem ini ditujukan Raffles agar menguntungkan penduduk pribumi dengan membebaskan mereka dari kerja paksa (rodi) dan kerja bakti lainnya agar mereka mampu membayar pajak tanah saja.
Faktanya seperti diungkap oleh Peter Carey, dalam buku The power of prophecy Prince Dipanagara and the end of an older in Java, 1785-1855, menjelaskan bahwa para penduduk tetap diwajibkan bekerja paksa menanam kopi dan tanaman indigofera dengan beban kerja yang mampu membuat kulit mereka berubah (discoloration of their skin). Akan tetapi upah yang diberikan kepada mereka tergolong rendah–bahkan saking rendahnya apabila kita menggunakan ukuran saat ini juga akan terheran-heran.
Sistem yang dibuat Raffles itu nyatanya tidak melepaskan penderitaan rakyat. Sebab penderitaan rakyat tidak cukup sampai di situ. Salah satunya kewajiban pajak ini juga dibebankan seluruhnya kepada penduduk setempat. Hal ini diperkuat oleh seorang dari Prancis bernama Joseph Donatien Boutet yang memberikan laporan atas kunjungannya ke Kedhu dan Pekalongan mengenai kesulitan yang dialami petani di wilayah itu. “Petani dipaksa menjual tanaman komersial mereka yaitu tembakau untuk membayar pajak tanah. Jarang sekali petani memperoleh keuntungan dari hasil keringat mereka sendiri dikarenakan pajak tinggi yang pasti ditarik oleh para pengumpul pajak (demang)”. Sementara itu, meskipun sudah digaji oleh pemerintah kolonial, para Bupati masih berusaha memperoleh keuntungan dengan cara memeras petani untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Pemerintah kolonial membiarkan praktik ini karena para Bupati lah yang menjaga ketertiban dan kestabilan struktur hierarkis masyarakat di daerah, dengan demikian sistem ekonomi yang mereka rencanakan berjalan lancar. Dengan kata lain, kenyataan masyarakat Indonesia di masa kolonial tidak jauh berbeda dibanding setelah bangsa ini setelah merdeka. Dalam koran Algemeen Handelsblad voor Nederlansche-Indie yang terbit pada tanggal 4 Februari 1936 di Semarang melaporkan praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di daerah Bojonegoro dengan headline “Fraude in Bodjonegoro”. Dalam laporan koran tersebut mengatakan para pejabat di kabupaten Bojonegoro telah bersekongkol untuk mengotak-atik anggaran, ironisnya hampir semua pejabat yang melakukan perbuatan ini mendapat promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi (Nagenoeg alle ambtenaren, ressorteerende onder dien raad, zij in meerdere of mindere mate gecompromitteerd). Pengelolaan lembaga kabupaten dan yang berada di bawahnya itu dalam kendali mereka dan uang rakyat sudah pasti dikonsumsi demi kepentingan mereka sendiri (veel geld moet zijn opgesoupeerd, dat toekwam aan de bevolking).
Akhir koran tersebut mewartakan tentang Bupati itu sendiri “Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia hidup seperti seorang raja. Buktinya, ia memelihara enam istri, memiliki tiga mobil, dan memiliki toko dalam jumlah banyak yang satu tokonya bernilai seribu gulden” (Ten bewijze hiervan wordt aangevoerd, dat hij er zes bij vrouwen op na hield, in het bezit was van drie auto’s, terwijl zijn toko-rekeningen maandelijks tot aanzienlijke bedragen opliepen ; men weet te Bodjonegoro te vertellen dat er een bij was van duizend gulden).
Apakah pejabat korupsi karena gaji kecil ?
Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat seringkali menimbulkan alasan apologetik. Ada anggapan maraknya kasus korupsi disebabkan karena gaji yang mereka peroleh sangatlah kecil dan tidak bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Implikasi dari anggapan ini adalah wajar jika para pejabat akan mencari penghasilan tambahan dengan menyalahgunakan kekuasaan seperti pungli, suap-menyuap, jual-beli jabatan dan izin usaha.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para pegawai pemerintah berupa gaji yang tinggi agar mereka fokus bekerja dan tidak perlu memikirkan besok makan apa, kebutuhan yang serba terpenuhi akan menutup celah pejabat untuk korupsi. Para koruptor berdalih bahwa negara-negara maju seperti Prancis, Jepang, dan Australia menerapkan ini.
Kendati demikian, apakah gaji besar mampu menahan hasrat pejabat untuk melakukan korupsi? kasus di masa kolonial dapat dijadikan pertimbangan.
Mari kita lihat alasan yang serupa, masih di koran berjudul Algemeen Handelsblad voor Nederlansche-Indie yang terbit pada tanggal 4 Februari 1936 di Semarang. Kali ini dengan headline yang berbeda “Het Dessahoofd”, yakni suatu peristiwa yang terjadi di Jawa Timur–tempatnya tidak disebutkan secara rinci.
Laporan dalam koran itu menyebutkan di abad ke-20 seorang kepala desa diberikan anggaran tambahan oleh pemerintah atas pengajuan dari Volksraad–Dewan Rakyat Hindia Belanda. Namun kepala desa tersebut masih mendapat penghasilan tambahan dengan menerima upah atas pengumpulan pajak, padahal dalam peraturan mereka tidak lagi boleh mencari keuntungan dari pemungutan pajak karena sudah digaji oleh pemerintah kolonial.
Melihat keadaan ini sang penulis berita kesal dengan tingkah laku pejabat di daerah dan menginginkan pemerintah kolonial untuk melakukan reformasi administrasi demi pemerintahan yang lebih baik di Jawa dan Madura, agar para pejabat dengan otoritas besar ini tidak lagi sewenang-wenang pada masyarakatnya yang buta huruf.
Sang penulis menyarankan agar pemerintah menggaji kepala desa dengan tanah bengkok dengan isi laporannya seperti ini: “Kami berterima kepada pemerintah atas anggaran tambahan yang dialokasikan kepada kepala desa, tetapi keadaan yang sehat tidak akan pernah muncul di desa, selama kepala desa tidak dibayar secara permanen dengan subsidi dari tanah oleh masyarakat yang bersangkutan”. (Wij zijn der Regeering dankbaar, maar een gezonde toestand zal in de dessa’s nooit onstaan, zoolang de dessahoofden niet op vasten voet met subsidie van het Land door de betrokken gemeenschappen bezoldigd worden)
Kasus di atas memperlihatkan bahwa gaji besar tidak memecahkan masalah mengenai perilaku pejabat yang masih nyari duit ke sana-sini dengan menyelewengkan jabatannya, meski telah mendapat gaji tetap dan tambahan anggaran. Jika kita tarik ke masa kita hidup saat ini, keadaan tidak jauh berbeda dari masa kolonial, pejabat berpangkat tinggi dengan gaji selangit adalah orang yang paling sering menggunakan kostum berwarna oren KPK.
Mungkinkah dari sananya?
Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa fenomena seperti di atas hingga saat ini terus berulang dan seakan sudah melekat pada birokrasi negara kita? Barangkali pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan merunut pada konsep negara tradisional bangsa Indonesia.
Ong Hok Ham dalam bukunya Wahyu yang Hilang Negeri Yang Goncang, merunut asal-usul ini karakter korupsi dan menyalahi kekuasaan jauh ke belakang, tepatnya ketika zaman kerajaan. Menurut Ong, di zaman kerajaan, raja melimpahkan kekuasaan daerah ke tangan pejabat. Raja tidak menggaji mereka tetapi pejabat diberi kekuasaan atas rakyat dan mereka mendapat penghasilan dari situ. Para pejabat rendahan menjadi perantara bagi rakyat yang memiliki kepentingan dengan penguasa, jika ingin urusannya lancar rakyat harus memberi persen pada pejabat.
Lakon Raden Adipati Danurejo IV sangat mencerminkan mental pejabat yang “ada duit baru jalan” alias mata duitan. Bupati Karanganyar yaitu Raden Adipati Jayadiningrat membahas perilaku korup ini dalam naskahnya :
“Agar perkara selesai segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo IV. Barangsiapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang, barang, atau perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang. Jika pihak yang kalah menolak menerima vonis, maka perkara yang lebih berat akan ditimpakan pada mereka atau akan difitnah bahwa orang itu memelihara perampok dan saksi-saksi yang mahir merekayasa bukti akan dipanggil. Pada akhirnya, pihak yang telah menolak vonis akan dihukum atau diwajibkan membayar denda.
Kadang kala mereka memperoleh penghasilan dari jual beli jabatan dan si pembeli akan menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa kontrol keuangan yang ketat menyebabkan penguasa daerah menjadi raja kecil dengan kekayaan melimpah. Raja di pusat dapat dikatakan menjadi bagian dari sistem ini, ia menikmati upeti yang diserahkan penguasa daerah padanya yang sumbernya tidak hanya berasal dari pajak tetapi juga pungli dan jual-beli jabatan. Singkatnya, pungli di zamannya adalah praktik yang dilegalkan raja sebagai sistem untuk menggaji pejabat di daerah.
Praktik ini terus berlangsung hingga abad ke-19 sebelum digantikan dengan sistem gaji karena dirasa tidak pantas bagi aparat birokrasi menjalankan tugas sambil mencari penghasilan tambahan. Bisa jadi inilah salah satu alasan yang menyebabkan mengapa para pejabat sering melakukan praktik korupsi. Pertama, ada alasan historis dan budaya yang berbeda untuk memisahkan hal-hal yang profesional untuk kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Kedua, pejabat korupsi bukan hanya besaran gaji yang diperoleh tetapi secara historis. Birokrasi negara Indonesia memungkinkan untuk melakukan tindakan seperti itu.
“The Power of Orang Dalam” pada Korupsi
Ada selorohan mengatakan hal yang paling penting bukanlah keahlian yang anda punya dalam suatu bidang, tetapi seberapa banyak relasi yang anda miliki dengan “orang dalam”. Masih lestarinya ungkapan seperti ini menunjukkan bangsa ini belum banyak berubah. Agenda reformasi yang berangkat dari keinginan untuk menghapuskan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi kenyataannya tetap menjangkiti Indonesia bahkan 25 tahun setelah Orde Baru runtuh. Kita akan lihat bagaimana keadaan saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.
Di masa Orde Baru, Soeharto melakukan monopoli seluruh sektor ekonomi negara untuk memperkaya keluarga beserta kroni-kroninya. Dengan sokongan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah, kroni dan keluarga Soeharto memperoleh kemudahan mengakses bisnis dan proyek-proyek dengan keuntungan besar.
Mitra tertua Soeharto, Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono memonopoli impor gandum dan tepung terigu pada 1969. Mereka menggunakan penyediaan gandum Amerika dengan program “Food for Peace” dari Amerika Serikat.
Kroni Soeharto lainnya, rekrutan Liem Sioe Liong yang kemudian menjadi pendiri dan pemimpin Lippo Group yaitu Mochtar Riady membangun Bank group Salim, Bank Central Asia (BCA) dengan kepemilikan saham sebanyak 17,5 % di BCA, sementara Tutut dan Sigit Hardjojudanto mendapat 30 %.
Anak-anak Soeharto sendiri memperoleh bagiannya masing-masing. Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut menjalankan bisnis tol. Bambang Trihatmodjo mendapat tempat di bisnis kimia dan satelit komunikasi, salah satu pemilik armada tanker minyak dan LNG terbesar di Asia. Tommy Soeharto mengambil proyek mobil nasional pertama Mobil Timor bekerja sama dengan KIA Motors, Korea Selatan. Sigit Hardjojudanto selaku anak paling tua memegang saham konglomerasi Tommy, grup Humpuss. Titiek Hariadi merupakan pemegang saham di Grup Tirtamas Comexindo milik adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Apa yang telah disebutkan hanyalah segelintir dari penguasaan lahan bisnis anak-anak Soeharto. Mereka sangat rakus dan saling bersaing untuk memperoleh mega proyek lainnya. Merunut pada keterangan yang diberikan oleh Jusuf Wanandi dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, Benny Moerdani yang memang diberi kepercayaan oleh Soeharto untuk mengurusi anak-anaknya, merasa terganggu dengan keserakahan anak-anaknya hingga ia memutuskan untuk mengurangi jumlah proyek yang mereka dapatkan. Mereka akhirnya memperoleh jatah proyek tidak seperti biasanya, akhirnya mereka mengadu pada bapaknya, Soeharto. Konon hal ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa Benny Moerdani dibuang oleh Soeharto setelah 14 tahun mengabdi setia. Terlalu merecoki dan mengganggu kepentingan anaknya.
Soeharto tentunya melibatkan elemen politik lainnya dalam praktik monopolinya; aparatur keamanan negara dan elit-elit politik dalam partai. George Junus Aditjondro dalam buku Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa mengatakan Soeharto mengelola sektor ekonomi negara dan swasta di Indonesia seperti satu keluarga besar. Di dalamnya hubungan sipil dan militer terjalin sangat mesra. Di sisi lain, elit politik melalui partai penguasa, dalam kasus ini Golkar, menjadi pelindung kepentingan bisnis keluarga istana.
Setelah Soeharto lengser dan Habibie naik ke tampuk kekuasaan, keadaan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Keluarga Habibie menggeser peranan keluarga Soeharto dalam ekspansi bisnis oligarki. Misalnya, dalam kegiatan pengeksporan pasir laut dari Kepulauan Riau ke Singapura. Di masa Soeharto, pastilah dipimpin oleh Tommy Soeharto dan Anthony Salim. Saat Habibie berkuasa, proyek ini pindah ke tangan Thariq Kemal Habibie.
Di era Gus Dur yang singkat, ia tidak bisa menahan kronisme para pendukungnya yang berasal dari NU dan PKB. Skandal Buloggate I, orang-orang terdekat Gus Dur mengantongi uang sebanyak Rp 35 miliar dari Yayasan Bina Sejahtera yang merupakan dana tabungan pensiunan karyawan Bulog. Selain kasus Buloggate, kasus Bruneigate juga menjadi bahan untuk menggulingkan Gus Dur dari kekuasaan. Berhentinya Gus Dur digantikan oleh Megawati. Kurang lebih sama, di era kepemimpinannya ia pernah melakukan kontrak pembelian pesawat Sukhoi 30 K dari Rusia. Dalam proyek pembelian ini, anak perempuannya Puan Maharani diduga mendapat komisi sebesar 426, 4 miliar rupiah.
Dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia belum mengalami pergeseran dari tradisi KKN sejak Orde Baru-bahkan masa SBY dan Jokowi yang tidak perlu repot-repot dijelaskan. Lalu mengapa bangsa Indonesia, meskipun telah melakukan berbagai macam cara, selalu terjebak pada tradisi oligarki.
Dengan menggunakan perspektif historis, kebiasaan ini sebetulnya mengakar pada kebudayaan feodalistik Jawa. Benedict Anderson dalam buku Language and Power menjelaskan struktur administratif kerajaan Jawa sebelum zaman penjajahan adalah patrimonial. Konsepsi ini membentuk model pemerintahan sebagai perluasan keluarga-rumah tangga penguasa. Semua kekuasaan mengalir langsung dari penguasa, seseorang dimungkinkan mendapat kedudukan yang signifikan hanya apabila ia mengikatkan diri dengan sang penguasa sebagai pusat dari segala-galanya. Konsepsi seperti ini yang menjelaskan alasan mengapa penguasa selalu mendahulukan orang-orang yang lebih dekat dengannya, entah itu keluarga maupun kroni-kroninya. Hubungan personal dengan “orang dalam” lebih dipentingkan ketimbang profesionalitas. Tidak ada pemisahan antara wilayah publik dan privat.
Lalu apa solusinya ?
Setelah mengetahui kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, timbul pertanyaan apakah ada jalan keluar bagi permasalahan ini? Mengingat korupsi ini merupakan salah satu persoalan bangsa yang sangat ruwet.
Pertama-tama yang bisa dilakukan adalah revolusi mental. Mari kita berkaca pada Inggris. Dinasti politik, persekongkolan antara eksekutif dan parlemen, korupsi yang melembaga, serta pejabat yang memperkaya diri sendiri adalah permasalahan yang pernah dihadapi oleh Inggris di abad ke-18 yang disebut “Abad ke-18 yang panjang”. Paradigma seperti ini mulai bergeser di kalangan elit politik setelah adanya revolusi mental yang dilakukan kaum Injil yang menekankan nilai-nilai kejujuran, integritas dan kebanggaan melaksanakan tugas politik dengan jujur. Hasil buah pikiran Jeremy Bentham dan Samuel Bentham, filsafat moral, juga memiliki dampak pada elit politik dan masyarakat lebih luas. Bentham bersaudara menyuarakan utilitarianisme, sebuah laku yang mengedepankan sifat hemat, efisiensi, kebersahajaan dan integritas. Hal ini sontak mendorong reformasi di kalangan partai politik Inggris untuk membongkar sistem politik lama yang beranggapan bahwa pejabat pemerintah masih memiliki hak milik pribadi dan boleh mengambil “biaya tambahan” meskipun telah memperoleh gaji yang cukup. Bertolak dari sikap utilitarian ini, komisi kerajaan (Royal Commissions) pada tahun 1850 membenahi institusi-institusi penting birokrasi, seperti Angkatan Darat dan Universitas Oxford dan Cambridge yang pernah dilanda korupsi.
Hal kedua adalah faktor hukuman. Banyak pihak yang telah mengetahui jika korupsi itu merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Namun jeratan hukuman yang diberikan kepada para koruptor menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus korupsi-seringkali hukuman ringan diberikan karena pelaku merupakan orang yang dekat dengan penguasa. Tidak adanya sistem hukum yang menimbulkan efek jera, membuat para pejabat tidak kapok-kapoknya terus melakukan korupsi. Alhasil, untuk kesekian kalinya, negara harus menanggung kerugian finansial yang ditimbulkan oleh para pencuri uang rakyat ini.
Lagi-lagi kita perlu berkaca pada Inggris dalam menanggulangi perkara ini. Seorang elit politik bernama Thomas Parker yang menduduki jabatan Lord Chancellor, pada tahun 1724 diduga menerima suap yang setara dengan 255 miliar rupiah masa kini. Meskipun Thomas merupakan teman baik Raja Inggris, George I, Ia tetap diadili secara profesional. Atas perbuatannya, ia harus melepas jabatannya dan membayar denda tiga kali lipat dari harta korup yang ia terima sekitar 755 miliar rupiah uang sekarang. Ia juga ditahan dalam penjara khusus pengkhianat negara, Tower of London. Hingga ganti rugi itu lunas, semua harta dan aset Thomas Parker habis disita oleh negara. Dari sini dua hal dapat kita jadikan contoh. Pertama, hukuman untuk memberantas korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, meskipun pada seorang elit politik yang memiliki hubungan dengan kekuasaan, hukum dijunjung tinggi di atas segala-galanya, supremasi hukum. Kedua, hukuman yang diberikan harus proporsional, setimpal dengan kerugian yang telah disebabkan oleh koruptor. Lebih lanjut lagi, Rimawan Pradipto selaku pengamat korupsi menyatakan hak politik koruptor harus dicabut agar tidak dapat terjun menjadi pejabat publik dan ranah pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan sektor publik.
Referensi
Aditjondro, G. Y. (2006). Korupsi kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga. LKiS.
Algemeen Handelsblad voor Nederlansche-Indie. (1936, Februari 4). Het Dessahoofd dan Fraude in Bodjonegoro. Algemeen Handelsblad voor Nederlansche-Indie.
Anderson, B. R.O.G. (2000). Kuasa Kata Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Mata Bangsa.
Carey, P., & Suhardiyoto. (2016). Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi. Komunitas Bambu.
Ham, O. H. (2018). Wahyu yang Hilang Negeri yang Goncang. KPG.
Peter Carey, the Power of Prophecy; Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855. Second Edition. Leiden: KITLV Press, 2008, XX + 970 Pp. [First Edition in 2007; Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenku